Oleh Mohamad Asrori Mulky
Nama Khalil Abdul Karim tidak bisa dikesampingkan dari pergulatan pemikiran pembaruan dalam Islam. Dia bisa ditempatkan sejajar dengan sejumlah pemikir raksasa seperti Mohamad Arkoun, Nasr Hamid Abu Zaed, Sayed Mahmud al Qimni, Muhammad Said al Asymawi, dan Abdullahi Ahmed Al Na’im.
Dia adalah pemikir yang berani menantang narasi dominan dalam
hukum Islam dengan pendekatan historis-kritis. Gagasannya tentang historisitas
syariah, kritik terhadap relasi kuasa, dan pentingnya kontekstualisasi hukum
Islam memberikan kontribusi besar dalam wacana reformasi Islam. Meski banyak
menuai kontroversi, pemikirannya tetap relevan dan terus menjadi bahan diskusi
dalam dunia akademik dan keislaman.
Saya sendiri mulai bersentuhan dengan pemikiran Khalil Abdul Karim
sekitar lima tahun lalu. Agak terlambat memang. Kala itu saya masih menempuh
pendidikan master di Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta. Dalam suatu waktu, secara tidak sengaja saya melihat buku
berjudul Hegemoni Quraisy: Agama, Budaya, Kekuasaan di perpustakaan.
Sekilas saya membaca dan langsung terpikat. Lalu saya meminjamnya untuk lebih
mendalami ide-ide brilian dari penulisnya.
Hegemoni Quraisy mengisahkan dominasi suku
Quraisy dalam menguasai Ka’bah dan Jazirah Arab sejak Qushoy bin Kilab hingga
imperium Islam. Khalil Abdul Karim menunjukkan kepada kita bagaiman seluruh
pemimpin Islam pasca-Nabi berasal dari Quraisy. Hasrat hegemonik suku Quraisy bahkan
kembali terlihat di hari di mana Nabi Muhammad wafat, yang kemudian umat Islam
berselisih soal suksesi. Alhasil kelompok Anshor harus merelakan kepemimpinan
umat Islam kepada Muhajirin hanya karena mereka bukan suku Quraisy.
Hasrat Hegemonik Quraisy ini, menurut Ibnu Khaldun seperti terurai
dalam karya agungnya, Muqodimah, merupakan pantulan dari budaya tribalistik (‘ashabiah)
yang mengakar dalam dalam kehidupan mereka. Bahkan hingga kini hasrat kesukuan
itu masih tertanam dalam kehidupan masyarakat Arab modern. Hal ini bisa kita
saksikan dari penamaan rezim kekuasaan Arab modern selalu merujuk pada
kebesaran klan tertentu.
Khalil Abdul Karim melanjutkan proyek
intelektualnya dengan menulis buku Daulah Yatsrib: Basâ’ir fî ‘Âm al Wufûd
(Negara Madinah: Politik Penaklukan Masyarakat Suku Arab). Buku ini bisa
dikatakan lanjutan dari Hegemoni Quraisy. Buku Negara Madinah mengisahkan
realitas masyarakat Madinah pada zaman Nabi, di mana orang Arab berduyun-duyun
datang ke Madinah hanya untuk mengagungkan suku Quraisy bukan Islam.
Tidak lama Nabi Muhammad wafat suku-suku Baduy
Arab melepaskan diri satu persatu sebagai wujud pembangkangan mereka terhadap
kekuasaan Islam yang dipimpin Abu Bakar.
Mereka memilih kembali ke agama nenek moyang masa lalu mereka dengan meninggal
Islam. Dan karena itu mereka tidak mau membayar zakat. Lalu Abu Bakar bereaksi
dengan memerangi mereka karena dianggap sudah membelot.
Khalil Abdul Karim (1930-2002) lahir di Mesir dan tumbuh dalam
lingkungan yang kental dengan tradisi Islam. Dia menempuh pendidikan dalam
bidang hukum dan syari’ah, yang kemudian membawanya pada kajian mendalam
mengenai sejarah Islam. Sebagai seorang akademisi dan penulis progresif, dia
dikenal aktif dalam meneliti serta mengkritisi peran kekuasaan dalam
pembentukan hukum Islam dan syariah.
Gagasan Khalil Abdul Karim tentang historisitas
syariah yang mustahil dilepaskan dari konteks sosial, politik, dan ekonomi, menuai
reaksi hebat dari kalangan Islam tradisionalis-konservatif. Pandangannya itu
dianggap telah menggetarkan bangunan dogma agama yang sebelumnya dipandang kokoh
tegak berdiri. Dan kini, banguan itu tidak sekedar bergetar. Malah telah roboh.
Porak bersama reruntuhan dogma agama.
Syariah Islam yang dianggap mapan dan sempurna oleh
Khalil Abdul Karim mulai ditinjau kembali. Dia menekankan syariah bukanlah
sesuatu yang turun dari langit tanpa campur tangan manusia, melainkan produk
sejarah yang terbentuk dalam konteks sosial dan politik tertentu. Sehingga
sulit melepaskan syariah sebagai teks yang statis dari konteksnya yang terus
dinamis.
Upaya Khalil Abdul Karim meninjau ulang pemaknaan syariah sebagai
reaksi dari problematika yang dihadapi umat Islam dewasa ini. Umat Islam kini
tengah menghadapi tantangan dinamika kontemporer yang sangat kompleks. Respon
yang kerap muncul di permukaan adalah devensif-apologetik dan tindakan yang
kontra-produktif. Akibatnya, sebagian umat Islam semakin terkungkung dalam
kondisi yang memprihatinkan. Sebagian telah melakukan ijtihad, tetapi belum
semaksimal umat dan bangsa lain.
Sebenarnya, umat Islam bukannya tidak melakukan ijtihad sama
sekali. Mereka telah melakukannya, tetapi sebatas pembacaan yang berulang-ulang
(al qira’ah al mutakarrirah), mereka kurang atau tidak berani melakukan
ijtihad yang baru (al qira’ah al muntijah). Inilah yang menjadi motivasi
Khalil Abdul Karim melakukan peninjauan ulang terhadap syariah yang kadung
dianggap ahistoris yang banyak menyumbang kemunduran umat Islam.
Apa yang diijtihadkan Khalil Abdul Karim
mendapat apresiasi dari Mohammed Arkoun. Filsuf Aljazair ini menegaskan apa
yang telah dilakukan Khalil Abdul Karim merupakan upaya dekonstruksi terhadap
otoritas hukum Islam klasik yang dianggap sakral dan abadi. Khalil Abdul Karim berusaha
mengembalikan ruh syariah yang bersifat dinamis dan progresif sebagaimana
kemunculannya di awal permulaan Islam.
Al
‘Arabu Mâdatul al Islâm (Arab adalah bahan baku Islam). Demikian Khalil
Abdul Karim mengatakan dalam al Judzûr al Târîkhiyyah li al Syarî’ah al
Islâmiyyah. Kitab tersebut menuai reaksi hebat dari kalangan tradisionalis-konservatif.
Melalui karya pertamanya itu, Khalil Abdul Karim memosisikan syariah tidak lahir dalam ruang
hampa, tetapi dalam konteks tertentu yang sangat dipengaruhi dinamika
kekuasaan.
Paling tidak ada empat hal yang hendak disampaikan Khalil Abdul
Karim dalam karyanya tersebut. Pertama, suka tidak suka konsep syariah telah
menjadi arena perdebatan berbagai kelompok dalam Islam. Celakanya, beragam
pemaknaan terhadap hukum Islam itu sering kali dipengaruhi oleh kepentingan
politik dan sosial yang berbeda.
Kedua, kekuasaan punya andil dalam menentukan pemaknaan syariah. Demi
melestarikan posisi penguasa tidak jarang menggunakan tafsir tertentu. Dan itu
dilakukan dengan cara menekan oposisi agar legitimasi kekuasaannya tetap aman. Ketiga
adalah bahwa pemahaman terhadap syariah tidak dapat dilepaskan dari
perkembangan masyarakat. Setiap zaman memiliki tantangan dan kondisi sosial
tersendiri yang menyebabkan perubahan dalam tafsir hukum Islam.
Dan keempat adalah kritik terhadap pendekatan tekstualis
yang cenderung mengabaikan konteks sejarah dalam memahami syariah. Dalam hal
ini, Khalil Abdul Karim menekankan pentingnya pendekatan historis dalam melihat
bagaimana hukum Islam diterapkan dan ditafsirkan sepanjang sejarah.
al Judzûr al Târîkhiyyah li al Syarî’ah al
Islâmiyyah memberikan wawasan luas mengenai
bagaimana syari’ah dipahami dan diperdebatkan sepanjang sejarah. Dengan
pendekatan historis dan kritisnya, Khalil Abdul Karim berhasil mengungkap
dinamika pemaknaan syari’ah yang terus berubah seiring waktu dan diperebutkan
oleh banyak kekuatan yang berkepentingan. Buku ini memotret kompleksitas tafsir
hukum Islam dalam berbagai konteks sosial dan politik.
Dengan melakukan pendekatan kritis dan historis terhadap hukum
Islam dan syariah, Khalil Abdul Karim menantang pandangan tradisionalis-konservatif
yang menempatkan syariah sebagai yang ajeg dan konstan. Pemikirannya banyak
menuai kontroversi, terutama di kalangan tradisionalis-konservatif, tetapi juga
membuka ruang dialog yang lebih luas dalam memahami Islam secara benar dan holistik.
Dalam kajian kritis dan mendalam, Khalil menemukan bahwa begitu banyak
aspek religi atau peribadatan dari masyarakat jahiliyah diadopsi Islam. Sebut
saja misalnya haji, umrah, pengkultusan Ka’bah, pengagungan Ramadhan, kesucian
bulan-bulan Haram, tradisi jum’at, perbudakan, poligami, potong tangan, rajam hingga
persoalan qishas. Semua itu adalah warisan Islam dari peninggalan bangsa Arab.
Lalu kita bertanya, adakah Islam otentik jika kenyataannya ia
berasal dari tradisi lokal Arab pra-Islam?
“Dalam soal ini, Islam mengadopsi
sebagian sistem Jahiliah dan mencampakkan sebagian sistem yang lain. Terkadang
Islam memodifikasi sistem tersebut dengan pola penambahan atau pengurangan.
Tetapi pada saat yang lain Islam memakainya secara utuh tanpa modifikasi,
melainkan hanya sekedar mengganti nama semata”.
Apa yang disimpulkan Khalil dengan sendirinya mengusik kelompok
Islam konservatif yang berpendirian tekstualis dan dogmatis. Bagi mereka,
syariah itu suci sebab berasal dari Yang Suci, yaitu Allah SWT. Dan karena
syariah berasal dari Allah SWT maka (syariah) sempurna dan abadi meski telah
masuk dalam dimensi ruang dan waktu yang pofan.
Di sinilah letak kekeliruan kelompok Islam konservatif dalam
melihat syariah. Menurut Khalil, ketika syariah dianggap abadi dan telah
sempurna akan berdampak pada terhambatnya lapangan ijtihad bagi umat Islam. Dan
ini akan menyulitkan umat Islam sendiri untuk menjadi umat yang ideal yang bisa
bersaing dengan umat lain.
Pada mulanya watak dasar syariah adalah progresif dan dinamis,
bahkan revolusioner. Tapi sejak zaman keterpakuan (taqlîd) ia berpaling menjadi
alat untuk membatasi akal dan membekukan kretivitas umat dalam berijtihad.
Kegagalan umat Islam dalam ijtihad, disimpulkan futurolog Islam asal Inggris,
Ziauddin Sardar, karena menyakralkan syariah sebagai yang permanen dan abadi. Sardar
menyebutnya sebagai “malapetaka metafisis”.
Historisitas syariah yang diupayakan Khalil Abdul Karim saya kira
dalam upaya melepaskan umat Islam dari belenggu “malapetaka metafisis”
seperti yang dikatakan Ziauddin Sardar itu.




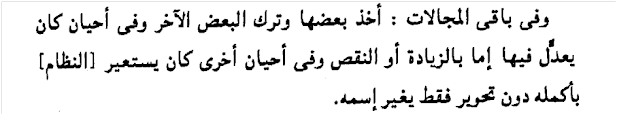











Tidak ada komentar:
Posting Komentar